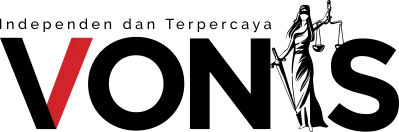VONIS.ID – Kekhawatiran mengenai menguatnya praktik militerisme di ruang sipil kembali mencuat dalam diskusi publik bertajuk “Hubungan Sipil dan Militer dalam Demokrasi: Menguatnya Militerisme dan Ancaman Kebebasan”yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, bekerja sama dengan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (SAKSI FH Unmul) dan Jurnal PRISMA. Acara ini berlangsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (UNMUL) dan dibuka langsung oleh Dekan FH UNMUL, Dr. Rosmini.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara yang menyoroti berbagai gejala kembalinya militerisme dalam kehidupan demokrasi Indonesia, mulai dari ancaman terhadap kebebasan akademik, keterlibatan aparat dalam bisnis tambang, hingga diskriminasi dalam sistem peradilan militer yang dinilai mengikis prinsip supremasi sipil.
Pembicara pertama, Gina Sabrina dari Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, memaparkan kronologi gejala militerisme yang terekam dari 2018 hingga 2025.
Ia menjelaskan bahwa ancaman terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi bukan lagi wacana, melainkan kenyataan yang terus menguat.
Ia menyoroti berbagai peristiwa seperti penyitaan buku bertema komunisme oleh TNI pada 2018, peningkatan intensitas penjagaan prajurit TNI di aksi demonstrasi besar sejak 2019, hingga keterlibatan satuan elite seperti Koopsus dalam pengamanan pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
“Kita melihat pola sekuritisasi terhadap kritik publik semakin dominan. Aksi demonstrasi, forum diskusi, termasuk ruang akademik mulai diawasi dan diintervensi oleh aparat militer,” tegas Gina.
Ia juga menyoroti maraknya kerja sama antara TNI dengan kampus melalui MoU yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan akademik.
Intervensi terhadap diskusi mahasiswa saat pembahasan revisi UU TNI menjadi contoh nyata bagaimana ruang pendidikan tinggi tak lagi steril dari tekanan militer.
“Ketika kampus menjadi ruang yang membuat civitas akademika takut bersuara, maka kita sedang kehilangan salah satu pilar demokrasi,” tambahnya.
menyoroti fenomena menguatnya peran militer dalam kehidupan sipil dari perspektif sejarah politik.
Ia membandingkan dua presiden berlatar belakang berbeda, SBY yang seorang purnawirawan TNI, dan Jokowi yang berlatar sipil. Paradox pun muncul, kepemimpinan sipil justru membuka ruang militerisasi lebih besar.
“Kita menyaksikan praktik-praktik yang dulunya identik dengan Orde Baru mulai muncul lagi. Militer masuk ke urusan sipil, bahkan ke sektor bisnis dan sumber daya alam,” ujar Saiful.
Ia mencontohkan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam tambang ilegal dan penguasaan lahan kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang menurutnya memperlihatkan absennya batas tegas antara domain militer dan sipil.
“Luka sejarah masa lalu tidak boleh terulang. Demokrasi tidak boleh mundur dari prinsip supremasi sipil,” tegasnya.
Ketua SAKSI FH UNMUL, Orin Gusta Andini, fokus pada persoalan lain yang tak kalah penting: stagnasi reformasi peradilan militer. Ia menyebut bahwa pemisahan peradilan berdasarkan subjek hukum — militer dan sipil — telah menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi.
“Yang harus jadi dasar peradilan adalah tindak pidananya, bukan subjek hukumnya. Praktik ini membuat banyak pelanggaran oleh oknum militer berakhir dengan vonis ringan dan menciptakan impunitas,” tegas Orin.
Ia menyoroti kasus korupsi Basarnas sebagai contoh buruk bagaimana mekanisme peradilan militer dapat menarik kasus publik kembali ke ranah tertutup, sehingga mengancam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, negara-negara demokrasi seperti Inggris, Jerman, dan Australia telah mengadopsi sistem peradilan berbasis tindak pidana, bukan profesi pelaku. Indonesia seharusnya segera melakukan reformasi serupa.
Peringatan lebih keras disampaikan oleh Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada di bawah ancaman serius rekonsolidasi militerisme di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ada lebih dari 133 MoU antara TNI dan berbagai kementerian/lembaga yang memperluas peran militer dalam sektor-sektor non-pertahanan. Ini jelas menyalahi UU TNI dan mengikis supremasi sipil,” jelas Ardi.
Ia menilai, kondisi tersebut menghidupkan kembali pola lama era Orde Baru ketika militer menjadi aktor dominan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Ardi juga mengingatkan bahwa lonjakan anggaran pertahanan di 2025 hingga Rp247,5 triliun tanpa mekanisme kontrol publik yang memadai adalah sinyal jelas bahwa orientasi negara sedang bergeser dari kesejahteraan menuju politik stabilitas dan kontrol.
“Jika kecenderungan ini tidak dihentikan, ruang kebebasan sipil akan makin sempit, dan demokrasi bisa tergerus dari dalam,” tegasnya. (tim redaksi)